Mungkin inilah rute terpanjang yang kami lewati setelah sebelumnya. Jalan terasa hanya milik kami berempat. Saya telah merampungkan tugas di Kota Buntok, kami menuju Palangkaraya yang dibuka dengan jembatan dan aspal mulus yang sempit.
Jika disandingkan, suasana ini mirip sekali jalur Sungai Gampa menuju Marabahan. Itu pada awalnya. Kita tak pernah tahu bagaimana suasana jalan di tengah-tengahnya.
Tidak ada kesempatan saya membuka google maps. Setelah disadari, posisi kami jauh sekali dari pemukiman. Dan ini bukan hutan rimbun. Melainkan hutan kering dan rawa. Sedikit gersang. Di pertengahan jalan banyak sekali saya lihat pepohonan hitam kering yang menjulang tinggi dibandingkan tanaman di sekelilingnya. Pemandangan di sekitar kami selalu berubah-rubah setiap 1 sampai 2 Km jauhnya.
Melaju dengan tenangnya, stay control. Hanya ada beberapa buah sepeda motor dan mobil saja yang melintas berlawanan arah atau mengejar dari belakang. Boleh dibilang, jalan raya ini sepi sekali. Sangat sepi. (Flashback ke catatan pertama, saya banyak sekali berfoto di atas motor ketika ini, karena tidak sempat memostingnya, saya kehilangan file foto tersebut).
Sejauh mata memandang, sejauh itu pula lah jalan yang terlihat di depan. Kadang kami mendapati tugu-tugu perbatasan wilayah kabupaten. Keluarlah kami dari Barito Timur, kini memasuki Kabupaten Barito Selatan.
Dear pembaca budiman, pernahkah kalian mendengar salah satu lirik lagu dari grup music bernamakan Payung Teduh.
Parararara.. Parararara.. Parararara… Pararara…
Parararara.. Parararara.. Huuuu…uuu….
Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap
Tapi aku tak bisa melihat matamu
Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur
Aku ingin berdua denganmu tapi aku hanya melihat keresahanmu
Parararara.. Parararara.. Parararara… Pararara…
Parararara.. Parararara.. Huuu.. Huuu…
Aku menunggu dengan sabar di atas sini melayang-layang
Tergoyang angin menantikan tubuh itu.
Di mana relasinya? Tidak ada. Hanya saja, ketika membaca salah satu plang penunjuk arah dari Dinas Perhubungan, saya mendapati Desa Bernama Pararapak. Mirip kan?

Pararapak adalah sebuah desa yang termasuk dalam Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dari jalan raya saja, Desa ini nampak sepi sekali. Mungkin penduduknya hanya beberapa puluh ribu saja. Saking penasarannya setelah di kota, saya mencari tahu tentang desa ini.
Hanya numpang lewat. Tidak ada persinggahan yang layak di Desa ini. Kami terus melanjutkan perjalanan. Suasana udara yang nyaman dan matahari yang menyapa lembut di sebelah barat membawa perjalanan begitu menyenangkan. Dengan beberapa tikungan lembayung terasa asik sekali.

Ada sebuah tikungan tajam ke sebelah kiri yang mengagetkan kami. Seorang rider muda dengan Jupiter MX berwarna biru menikung seperti pembalap dari arah berlawanan (ngajak bersaing). Lagaknya sudah seperti Komeng dalam iklannya. Untunglah Bungker sebagai rider sigap ketika ini.
Sejenak kita tinggalkan Desa Pararapak dengan lirik lagunya. Perjalanan berlanjut dengan aspal yang tenang namun bergelombang. Aspal yang berbatu-batu dan berpasir putih. Aspal yang masih setengah jadi. Sampai-sampai aspal yang masih dalam pengerjaan. Ya, kami menemui proyek pengaspalan di tengah jalan ini. Pemandangan yang sangat asing dan sangat jauh dari keramaian. Gersang. Dan lagi, saya tak sempat memotonya walau sempat terpikirkan.
Kemudian kami mendapati plang dengan nama yang terasa akrab para penggemar Anime. Adalah Desa Madara, salah satu desa di wilayah kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya bilang, penggemar Naruto pasi tahu ini. Kami putuskan untuk berhenti dan berfoto di depan plang. Sekaligus isitrahat.

Pepohonan rindang menuju kegelapan seperti tampak di hadapan. Wajah matahari tinggal lagi setengahnya. Sebentar lagi Matahari tenggelam penuh. Kami sama sekali tidak melihat adanya penerangan jalan umum. Tiang dan kabel-kabelnya saja tidak ada.
Saya ingat angka digital pada arloji menunjukkan angka 18.05. Setelah beberapa kali melihat rumah-rumah berjejer lenggang, beserta rumah makan dan bis kota yang lewat, juga deretan kios menjual keperluan dan premium eceran, kami memasuki desa yang bernama Timpah.
“Bagaimana kalau kita mengopi sebentar?”
Tanyaku dengan jawaban yang dikembalikan “Terserah pian aja”. Kami berhenti di salah satu kios yang juga warung kopi. Membuka tangki bensin dan mengisi masing-masing dua liter. Dan saat membayar, baru kuketahui 1 liternya seharga Rp.9.000. Wajar, kan di tengah hutan. Check Point 5.

Kami menunggu matahari tenggelam penuh di sini dengan berbagai obrolan. Sebagai tanda agar para follower mengetahui saya sedang berada di mana, maka saya sempatkan berfoto dan memostingnya walau sudah mengetahui suasana alam mulai gelap. Check Point 5. Ini adalah tempat peristirahatan.
Ada seorang paruh baya yang membeli rokok di kios ini. Dia menyempatkan bertanya saat melihat penampilan kami berempat.
“Dari mana, De?”
“Tamiyang Layang. Ke Palangka. Apa masih jauh , Pak?”
“Ya sekitar 80 Km lebih lah,”
“Mungkin 2 jam perjalanan, ya?”
“Buat saya ya 1 jam saja sudah nyampe.” (Bapak ini menggunakan Kawasaki KLX).
“Di perjalanan lumayan terang, kan, Pak?”
“Ya gelap lah. Mana ada lampu jalan.” Jawabnya sembari menutup pembicaraan. Kami menguncapkan terima kasih dan ia mulai melaju dengan trailnya.
Obol memaparkan, perkiraan kami sampai ke pusat kota Palangkaraya sepaling cepat pukul 21.00. Itu juga paling cepat. Kini suasana alam sudah mengaru biru. Biru dalam artian sebenarnya.
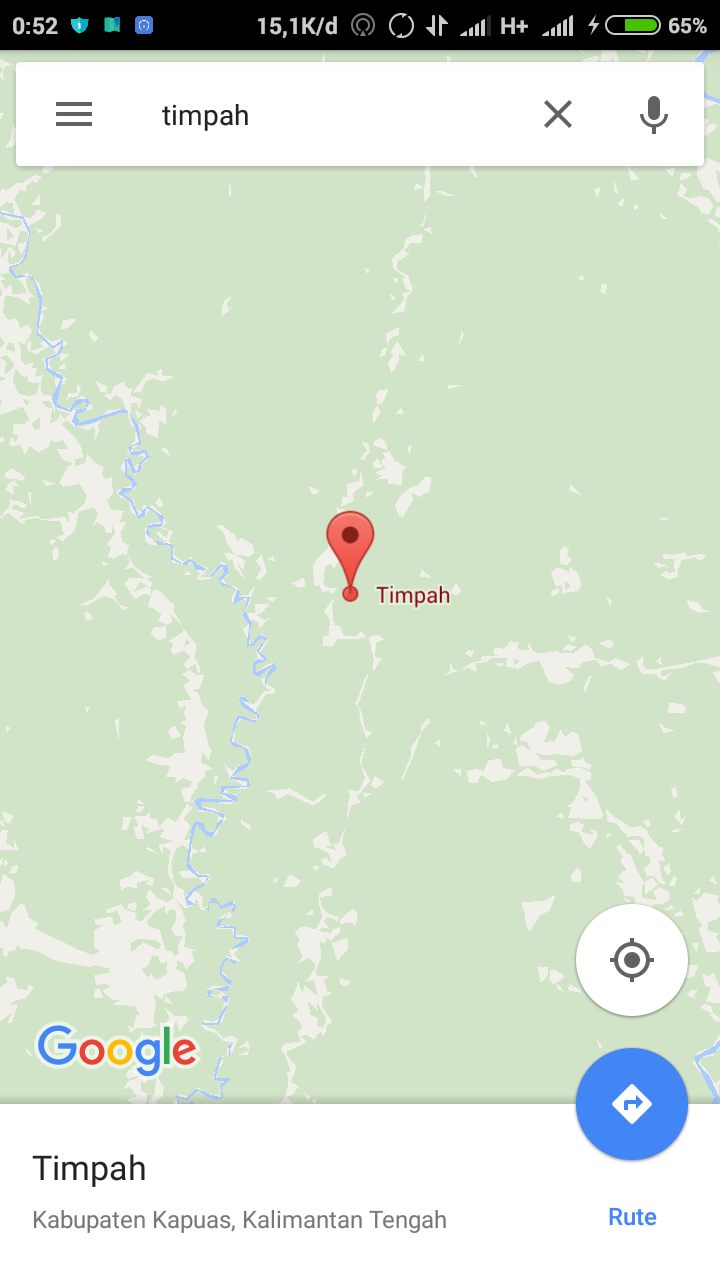
Usai memantapkan niat. Kami memulai perjalanan. Saya sebagai rider. Dear pembaca, saya rasa kios barusan yang kami singgahi adalah penghujung kampung. Selanjutnya gelap, tak ada lagi rumah berpenghuni. Saya tak sadar, lebih tepatnya tidak melihat apakah ada gubuk atau rumah lagi, karena sudah tidak ada lagi cahaya selain lampu depan dan belakang motor kami. Bahkan garis putih pada jalanan pun tak terlihat.
Perjalanan sudah sangat jauh. Jauh sekali. Terasa sangat dalam, entahlah, seperti ke dalam goa kesannya. Beberapa kali ada mobil dengan cepat melewati kami. Beberapa kali juga jembatan demi jembatan kami libas. Ada juga beberapa pengendara tanpa helm yang membawa kayu kami lewat. Lagi, tanpa penerangan sama sekali.
Berdasarkan efek saya sehari yang lalu, kemungkinan kantuk akan menyerang saya sekitar setengah jam lagi. Sembari tetap berkonsentrasi, saya sadari duduk Bungker tampak menjauh di belakang saya. Saya tepuk, dan berusaha seperti mengangkapnya. Prasangka, mungkin dia yang sempat tertidur. Dan sadar kembali bahwa sedang dalam perjalanan mencekam.
Tiba-tiba di pertengahan jalan, saat kecepatan sedang digeber, sekelibat kami melihat 2 orang pejalan kaki yang satunya mendorong sebuah motor Suzuki Satria F150 di sebelah kiri.
Saya dan bungker tampak sepemikiran. Memperlahankan maju motor. Dan memutuskan untuk kembali mendatangi dua orang tadi. Kasihan sekali dia, saya bergumam. Hanya ada dua kemungkinan, musibah bocor ban, atau kehabisan bensin. Bagaimana jika posisi tersebut menimpa pada kami?
“Kenapa?”.
“Habis minyak,” sahutnya.
“Ya sudah. Buat, aku dorong,” jawab saya sok kuat.
Ternyata, mendorong motor mogok yang ditunggangi 2 orang itu berat sekali. Mungkin belum 1 Km perjalanan 50km di tengah gelap malam, kaki kiri saya di pedal belakang terasa sangat nyeri. Sudahlah, saya putuskan bertukar joki saja.
Bungker ambil alih kemudi. Sembari saya menyeimbangkan di belakang. Saya menaruh kepercayaan penuh di sosok badan tegap layaknya prajurit ini. Jauh sekali ini. Membayangkannya mendorong motor itu sampai mendapati kios yang berjualan bensin, dan tanpa penerangan jalan sekali pun.
Proses itu memakan waktu kurang lebih 40 menit. Sampai kami mendapati kios berjualan bensin di pinggir sebelah kiri. Semoga ini kampung pembuka dari kampung-kampung berikutnya. Lumayan ada penerang di pinggir-pinggir jalan, kan.
“Mau di isi berapa liter?” Tanya saya.
“2,” jawabnya.
Saya melihat mimik ragu di wajahnya. Sangat tidak meyakinkan. Sedangkan satu kawannya lagi mengobrak-abrik ranselnya. Seperti mencari sesuatu yang memang tidak ada.
Saya berikan selembar uang yang tidak banyak.
“Ini untuk tambahan, semoga cukup,” ucap saya menyerahkan sembari berpesan agar hati-hati di jalan berikutnya. Kami berangkat meninggalkan paman yang menuangkan bensin di tangki mereka. Tak lupa ucapan terima kasih yang terdengar sayup tampak malu.
Ada beberapa obrolan yang terjadi sebelum, seperti pertanyaan perkenalan dan pertanyaan dari mana. Saya dan Bungker membicarakan hal yang sama. Motor termaksud memang bernopol DA. Tentu sama dari daerah kami berasal. Namun penampilan mereka bukan musafir dari luar daerah. Benar saja, keduanya mengaku dari desa yang tak jauh dari Timpah, pergi berangkat bekerja dan pulang dalam sehari saja.
Secara pribadi, tidak mungkin sebagai penduduk setempat tidak memperhitungkan jumlah bahan bakar yang mereka perlukan dalam sekali pulang dan pergi. Dan saya berprasangka kuat mereka memang sedang kehabisan uang. Terlepas prasangka itu mendekati kebenaran, Wallahualam.
“Tinggal berapa jam perjalanan lagi?”
“Ya tak jauh, setengah jam mungkin,”
“Sedikit lagi,”
Kami melaju dengan tenang. Sembari mengobrol beberapa. Kampung demi kampung belampu redup terlewati. Sampai kami mendapati plang besar penunjuk jalan yang bertuliskan Palangkaraya 45km. Kamu melaju berharap mendapati lampu-lampu perkotaan.
Sampai pada persimpangan tanpa penunjuk arah. Saya dan bungker berhenti di depan SPBU yang tututp menunggu Obol dan Haji Udin yang tertinggal jauh. Sembari membenarkan selangkangan, turun dari motor berganti joki lagi untuk merenggangkan otot-otot pinggang yang tegang.
Kami bertemu. “Masih jauh?”. “Parak ja, paling 10 menit lagi,” sahut Obol. Kuanggap itu sebagai penghibur saja. Bukankan kita sudah mengeja angka kilometer pada plang yang tampak terlihat.
Perjalanan terus melaju dengan beberapa tikungan tajam dan jembatan-jembatan lagi. Palangkaraya 29km, Palangkaraya 16km, Palangkaraya 7km, Palangkaraya blablabla. Sepanjagn jalan kami selalu terhibur dengan plang-plang penunjuk tersebut. Saya tak sabar menantikan warna-warni perkotaan, Obol bilang, sebagai pintu masuk, kami akan melewati Jembatan Kahayan yang berwarna-warni. Senang sekali mendengarnya.
Masa penantian itu pun tiba, hiruk pikuk lalu lintas berpolusi mulai terasa. Tampaknya, ini perbatasan Kabupaten, dan lihat di sana, warna-warni Jembatan Kahayan. Tampak muda-mudi berkendara hilir mudik, dan kami melewati Jembatan Kahayan dengan riang gembir.
Sampai di penghujung jembatan, memutar ke kanan dan berhenti di bawahnya. Persis di depan mural dan paman pentor terparki. Kami juga memarkir. Dan saya sempat berfoto sendiri di depan mural.
“Kita sudah sampai?”
“Ya, kita sudah di Palangkaraya,”
Belum ada ide kami akan kemana selanjutnya. Yang jelas sudah di Palangkaraya. Mungkin setelah ini ke tengah kota, melewati Kantor Gubernur dan DPRD, atau singgah di taman kota, atau… entahlah. Saya masih mati pikir dalam kondisi fisik sudah teramat lelah. Mata dan kepala sudah berat. Dan kami belum merencanakan… akan tidur di mana malam ini. Kutatap arloji, 21. 15. Kita tak pernah tahu. (bersambung)
menunggu season terakhiernya dah…
Siap